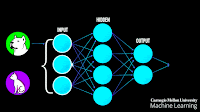14/04/2017
Kolaborasi Membangun Kampus WCU, Mungkinkah?
Syamsu Alam
Sejak kapan kosakata ‘Kolaborasi’ menghipnotis berbagai orang? Demikian pula frase World Class University (WCU) seolah frase ‘wajib’ disampaikan pada setiap sambutan di berbagai kampus? Mungkinkah kampus-kampus di Makassar mampu bersaing dan sejajar dengan kampua-kampus bertaraf internasional seperti UI dan Cambridge? Entahlah, mari dicek kemungkinannya ☺

Tentang mantra Kolaborasi dan WCU
Beberapa tahun terakhir tepatnya akhir 2006, perguruan tinggi di seantero nusantara bahkan di seluruh dunia berpacu mewujudkan WCU. Cita-cita tersebut ibarat ‘piala’ yang bisa direngkuh oleh setiap kampus yang berdaya saing tinggi dan memenuhi berbagai standar-standar sebagai WCU. Diantaranya akreditasi internasional, sebuah pengakuan terhadap kemampuan yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan yang berdaya saing internasional; kualitas pendidikan; kualitas pengajaran; dan infrastruktur perguruan tinggi. Para petinggi kampus menilai hal ini tidak mungkin dilakukan sendiri.
Kolaborasi kian populer menjelang Revolusi Industri keempat versi World Economic Forum (WEF), Sebuah revolusi baru ekonomi yang berbasis dan didorong oleh kemajuan teknologi digital. Pemicu utamanya bergesernya mode of production dari input modal fisik yang dominan ke input modal non-fisik (ide dan kreativitas), pemanfaatn input tersebut menjadikan berbagai perusahaan dan organisasi meraih sukses di pentas regional maupun global. Keberhasilan beberapa organisasi menjadi pemenang dengan strategi "Kolaborasi". Organisasi atau komunitas yang sukese diantaranya adalah Wikipedia, Facebook, Skype, Goldcorp, Linux, P&G dll.
Don Tapscott penulis The Digital Economy dan Wikinomics, mengungkapkan bahwa awalnya "Kolaborasi Maya" yang dilakukan oleh para netizen, programmer, youtuber dan lain-lain adalah semacam gerakan massif sebagai anti-tesa atas dominasi perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai media dam teknologi publikasi mainstream. Bahkan kerap dikatakan sebagai "komunisme gaya baru". Tetapi para aktivis "Kolaborasi Maya" tetap memacu kreativitas dan berinovasi tiada henti tanpa terpengaruh dengan stigma komunisme gaya baru. Misalnya Linux, yang awalnya hanyalah proyek "gotong-royong" dimana para programer berjejaring, berbagi source code, sharing pengalaman hingga akhirnya bisa bersaing dengan Microsoft atau Mac. Padahal tidak ada perusahaan yang menaunginya, toh, bisa menjadi pemain dan menguasai pangsa pasar dalam dunia Sistem Operasi. Hal yang sama terjadi pada perusahaan dan organisasi yang melakukan "Kolaborasi".
Dibalik mantra “Kolaborasi” tersirat semangat kemandirian, kerjasama sekaligus semangat berkompetisi melawan dominasi korporasi raksasa. Hal yang lebih penting dalam kolaborasi adalah praktik saling berbagi, saling percaya, dan transparansi.
Kolaborasi dan Feodalisme di Perguruan Tinggi
Berdasarkan sudut pandang perencanaan, kalaborasi dapat diidentikkan dengan proses, dimana inputnya adalah Mahasiswa, Dosen, Pegawai, Satpam, Stakeholder dan shareholder yang terkait dengan pengguna jasa dan produk (output) perguruan tinggi. Produk perguruan tinggi bisa berarti lulusan sarjana dan pascasarjana atau hasil kajian dan penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dimensi dampaknya (impact) adalah apakah produk tersebut dimanfaatkan sesuai kompetensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Jika Kolaborasi dimaknai seperti ini maka Tri Dharma Perguruan tinggi: pengajaran berlangsung demokratis, penelitian yang berkualitas karena dikerjakan dengan prinsip-prinsip kolaborasi (kerjasama, saling percaya, dan transparan) dan pengabdian pada masyarakat bisa lebih bermanfaat, dan tepat sasaran. Kolaborasi akan mampu mewujudkan sinergi antar civitas akademika yang pada akhirnya terwujud kampus sebagai "Center of Excellence". Tentu dengan berbagai konsekuensi dan perbaikan sistem kelembagaan yang mempraktikkan prinsip-prinsip kolaborasi.
Cerita sukses tentang organisasi/komunitas yang menerapkan Kolaborasi "Massif" sudah sangat banyak. Komunitas tersebut berani mentransformasikan sistem manajemennya. Organisasi yang awalnya menerapkan manajemen vertikal, model hirarkis yang ketat, berdasarkan komando, perintah atasan, dan standar operasional yang sangat kaku dan mekanistik, dapat menyebabkan bawahan terkena sindrom ABS (Asal Bos Senang). Dengan Kolaborasi, gaya tersebut ditransformasi menjadi Organisasi dengan sistem manajemen horisontal, terbuka, komunikasi lebih cair, fleksibel, penuh ruang improvisasi bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Dalam konteks perguruan tinggi, sistem seperti ini membuat jarak antara pejabat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi dengan yang bukan pejabat seperti dosen (pengajar semata), pegawai dan mahasiswa bisa dianggap tidak berjarak dan lebih terbuka.
Konsekuensi lebih jauh akan menghancurkan tatanan struktural feodalisme, entah feodalisme keturunan "karaeng", “raja”, "puan", “andi” atau feodalisme keilmuan "professor" dan bukan professor yang kerap menjangkiti perguruan tinggi. Tentu saja hal ini adalah alamat baik buat atmosfer akademik, dimana setiap civitas akademica adalah subjek dan ilmu pengetahuan adalah objeknya.
Konsekuensi selanjutnya, setelah struktur feodal runtuh, maka akan tercipta kesetaraan, ruang-ruang dialogis antar civitas akademika dan stakeholder makin luas. Dan pada akhirnya demokratisasi kampus dapat terwujud. Apakah semudah itu? Tentu tidak. Tapi yang pasti jika Kolaborasi telah menjadi kosakata pamungkas bagi sebagian besar petinggi kampus, maka semestinya prinsip-prinsip kolaborasi menjadi tonggak-tonggak pengelolaan perguruan tinggi.
Kolaborasi: Lipsing atau Inisiasi Masa Depan
Harapan terbesar kita sebagai masyarakat biasa pada para pemimpin perguruan tinggi dan kementerian pendidikan tinggi adalah satunya kata dan perbuatan atau dalam terminologi kampus adalah “kejujuran ilmiah”. Kolaborasi laiknya diperlakukan tidak seperti liberalisasi pasar, karena dalam liberalisasi menyimpan potensi laten ketimpangan dan penindasan bagi yang tidak punya akses dan asset pada sumber daya dan kekuasaan. Apalagi Negara kita adalah Negara berkembang dengan berbagai universitas masih terbelakang. Hayward (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa di Negara-negara berkembang diperlukan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan mental atas keinginan mewujudkan WCU. Yaa, perubahan mental. Merubah mental para pemimpin yang hirarkis dan kaku menjadi horisontal yang lebih terbuka bukan perkara mudah. Kolaborasi tentulah memuat prinsip pro-konsumer, tersedianya perpustakaan besar untuk berbagi sumber-sumber pengetahuan, terciptanya transparansi sebagaimana "kolaborasi maya" berbagi source code. Prasarat utama membangun kampus adalah menyuburkan pikiran kolaboratif bukan pikiran kolutif dan koruptif.

Tentang mantra Kolaborasi dan WCU
Beberapa tahun terakhir tepatnya akhir 2006, perguruan tinggi di seantero nusantara bahkan di seluruh dunia berpacu mewujudkan WCU. Cita-cita tersebut ibarat ‘piala’ yang bisa direngkuh oleh setiap kampus yang berdaya saing tinggi dan memenuhi berbagai standar-standar sebagai WCU. Diantaranya akreditasi internasional, sebuah pengakuan terhadap kemampuan yang memiliki desain dan kemampuan mencetak lulusan yang berdaya saing internasional; kualitas pendidikan; kualitas pengajaran; dan infrastruktur perguruan tinggi. Para petinggi kampus menilai hal ini tidak mungkin dilakukan sendiri.
Kolaborasi kian populer menjelang Revolusi Industri keempat versi World Economic Forum (WEF), Sebuah revolusi baru ekonomi yang berbasis dan didorong oleh kemajuan teknologi digital. Pemicu utamanya bergesernya mode of production dari input modal fisik yang dominan ke input modal non-fisik (ide dan kreativitas), pemanfaatn input tersebut menjadikan berbagai perusahaan dan organisasi meraih sukses di pentas regional maupun global. Keberhasilan beberapa organisasi menjadi pemenang dengan strategi "Kolaborasi". Organisasi atau komunitas yang sukese diantaranya adalah Wikipedia, Facebook, Skype, Goldcorp, Linux, P&G dll.
Don Tapscott penulis The Digital Economy dan Wikinomics, mengungkapkan bahwa awalnya "Kolaborasi Maya" yang dilakukan oleh para netizen, programmer, youtuber dan lain-lain adalah semacam gerakan massif sebagai anti-tesa atas dominasi perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai media dam teknologi publikasi mainstream. Bahkan kerap dikatakan sebagai "komunisme gaya baru". Tetapi para aktivis "Kolaborasi Maya" tetap memacu kreativitas dan berinovasi tiada henti tanpa terpengaruh dengan stigma komunisme gaya baru. Misalnya Linux, yang awalnya hanyalah proyek "gotong-royong" dimana para programer berjejaring, berbagi source code, sharing pengalaman hingga akhirnya bisa bersaing dengan Microsoft atau Mac. Padahal tidak ada perusahaan yang menaunginya, toh, bisa menjadi pemain dan menguasai pangsa pasar dalam dunia Sistem Operasi. Hal yang sama terjadi pada perusahaan dan organisasi yang melakukan "Kolaborasi".
Dibalik mantra “Kolaborasi” tersirat semangat kemandirian, kerjasama sekaligus semangat berkompetisi melawan dominasi korporasi raksasa. Hal yang lebih penting dalam kolaborasi adalah praktik saling berbagi, saling percaya, dan transparansi.
Kolaborasi dan Feodalisme di Perguruan Tinggi
Berdasarkan sudut pandang perencanaan, kalaborasi dapat diidentikkan dengan proses, dimana inputnya adalah Mahasiswa, Dosen, Pegawai, Satpam, Stakeholder dan shareholder yang terkait dengan pengguna jasa dan produk (output) perguruan tinggi. Produk perguruan tinggi bisa berarti lulusan sarjana dan pascasarjana atau hasil kajian dan penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, perusahaan, atau pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dimensi dampaknya (impact) adalah apakah produk tersebut dimanfaatkan sesuai kompetensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa. Jika Kolaborasi dimaknai seperti ini maka Tri Dharma Perguruan tinggi: pengajaran berlangsung demokratis, penelitian yang berkualitas karena dikerjakan dengan prinsip-prinsip kolaborasi (kerjasama, saling percaya, dan transparan) dan pengabdian pada masyarakat bisa lebih bermanfaat, dan tepat sasaran. Kolaborasi akan mampu mewujudkan sinergi antar civitas akademika yang pada akhirnya terwujud kampus sebagai "Center of Excellence". Tentu dengan berbagai konsekuensi dan perbaikan sistem kelembagaan yang mempraktikkan prinsip-prinsip kolaborasi.
Cerita sukses tentang organisasi/komunitas yang menerapkan Kolaborasi "Massif" sudah sangat banyak. Komunitas tersebut berani mentransformasikan sistem manajemennya. Organisasi yang awalnya menerapkan manajemen vertikal, model hirarkis yang ketat, berdasarkan komando, perintah atasan, dan standar operasional yang sangat kaku dan mekanistik, dapat menyebabkan bawahan terkena sindrom ABS (Asal Bos Senang). Dengan Kolaborasi, gaya tersebut ditransformasi menjadi Organisasi dengan sistem manajemen horisontal, terbuka, komunikasi lebih cair, fleksibel, penuh ruang improvisasi bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Dalam konteks perguruan tinggi, sistem seperti ini membuat jarak antara pejabat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Prodi dengan yang bukan pejabat seperti dosen (pengajar semata), pegawai dan mahasiswa bisa dianggap tidak berjarak dan lebih terbuka.
Konsekuensi lebih jauh akan menghancurkan tatanan struktural feodalisme, entah feodalisme keturunan "karaeng", “raja”, "puan", “andi” atau feodalisme keilmuan "professor" dan bukan professor yang kerap menjangkiti perguruan tinggi. Tentu saja hal ini adalah alamat baik buat atmosfer akademik, dimana setiap civitas akademica adalah subjek dan ilmu pengetahuan adalah objeknya.
Konsekuensi selanjutnya, setelah struktur feodal runtuh, maka akan tercipta kesetaraan, ruang-ruang dialogis antar civitas akademika dan stakeholder makin luas. Dan pada akhirnya demokratisasi kampus dapat terwujud. Apakah semudah itu? Tentu tidak. Tapi yang pasti jika Kolaborasi telah menjadi kosakata pamungkas bagi sebagian besar petinggi kampus, maka semestinya prinsip-prinsip kolaborasi menjadi tonggak-tonggak pengelolaan perguruan tinggi.
Kolaborasi: Lipsing atau Inisiasi Masa Depan
Harapan terbesar kita sebagai masyarakat biasa pada para pemimpin perguruan tinggi dan kementerian pendidikan tinggi adalah satunya kata dan perbuatan atau dalam terminologi kampus adalah “kejujuran ilmiah”. Kolaborasi laiknya diperlakukan tidak seperti liberalisasi pasar, karena dalam liberalisasi menyimpan potensi laten ketimpangan dan penindasan bagi yang tidak punya akses dan asset pada sumber daya dan kekuasaan. Apalagi Negara kita adalah Negara berkembang dengan berbagai universitas masih terbelakang. Hayward (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa di Negara-negara berkembang diperlukan perubahan yang mendasar, yaitu perubahan mental atas keinginan mewujudkan WCU. Yaa, perubahan mental. Merubah mental para pemimpin yang hirarkis dan kaku menjadi horisontal yang lebih terbuka bukan perkara mudah. Kolaborasi tentulah memuat prinsip pro-konsumer, tersedianya perpustakaan besar untuk berbagi sumber-sumber pengetahuan, terciptanya transparansi sebagaimana "kolaborasi maya" berbagi source code. Prasarat utama membangun kampus adalah menyuburkan pikiran kolaboratif bukan pikiran kolutif dan koruptif.