13/05/2012
7 Mitos Penghambat Kemandirian
TORAWARENAI SUNAONA KOKORO
(Pikiran yang Tidak Melekat)
oleh Dr.Ir. Dimitri Mahayana, M.Sc.
7 Mitos Penghambat Kemandirian. Entah angin apa yang mengantar saya pada Folder koleksi Artikel, dan menemukan tulisan yang menurut saya inspirasi untuk membangun kemandirian personal maupun bangsa. Tulisan sederhana yang senantiasa menyemangati gerak keseharian kita, khususnya bagi pebisnis, akademisi, intelektual, "politisi", petualang dan siapapun yang ingin belajar dan berpikiran maju. Judul postingan, adalah murni subjektifitas saya (alamyin) tidak ada maksud selain berbagi inspirasi. Selamat membaca.
Judul asli tulisan ini adalah TORAWARENAI SUNAONA KOKORO (Pikiran yang Tidak Melekat) ditulis oleh Dr.Ir. Dimitri Mahayana, M.Sc.
Konosuke Matsushita, pendiri korporasi raksasa Jepang Matshushita, mempunyai satu prinsip filosofis manajemen yang amat terkenal; "Torowarenai sunaona kokoro, (pikiran [hati] yang tidak melekat)". Matsushita yakin seorang pemimpin harus benar-benar memiliki kebeningan hati, kecerahan pikiran, dan ke-tidakmelekat-an pikiran dan hati agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat.
Kemelekatan IBM dengan industri komputer mainframe-nya, misalnya, telah membuat para pimpinannya membatasi penjualan PC (Personal Computer) - yang dikhawatirkan akan merusak pasar komputer mainframe- sehingga akhirnya IBM tidak bisa leading dalam industri PC di dunia, padahal ia termasuk yang paling awal menguasai teknologi PC. Dan apa yang terjadi? PC ternyata menjadi satu dengan kehidupan masyarakat global. IBM telah menyia-nyiakan pasar masa depan hanya karena kemelekatannya dengan masa lalunya. Berpikir tentang krisis moneter akhir-akhir ini ala Matsushita, kita mesti meninggalkan ke-melekat-an pikiran dan persepsi bangsa atas beberapa aspek berikut.
Pertama, kemelekatan atas bayangan-bayangan "sukses" pembangunan nasional di masa sebelum krisis.
Analisis-analisis para pakar ekonomi dari Bank Dunia, IMF, telah lama meninabobokkan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan angka-angka yang fantastis. Mereka mensugesti Indonesia dengan "kenyataan" bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 7 hingga 8% setahun dengan laju inflasi kurang dari dua digit. Bangsa Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lain mesti melepaskan diri dari khayalan-khayalan "sukses" semacam ini, dan segera menyadari kondisi objektif yang benar-benar riil. Dengan kesadaran ini, kejernihan melakukan langkah yang tepat dalam menanggulangi krisis dapat diperoleh.
Kedua, kemelekatan pada nowism (kekinian) dan menyibukkan diri dengan melihat kurs dolar maupun jumlah orang yang di-PHK tiap hari dan merenungkannya, kemudian menenggelamkan diri dengan berbagai isu-isu dan rumor-rumor yang tidak jelas arah dan sumbernya.
Akan sangat banyak energi yang terbuang sia-sia jika bangsa ini terjebak pada pola over-analysis dan over-observation sehingga malah tidak segera mengambil tindakan apa pun. Apakah dengan nilai dolar setiap hari berubah, seorang bussinesmen mesti mengubah bisnisnya setiap hari? Atau apakah semua orang mesti terjun beramai-ramai bermain valas, sehingga bangsa akan memakan dolar sebagai ganti beras? Apakah dengan menangisi orang-orang yang di-PHK semuanya akan beres?
Ketiga, kemelekatan pada ketergesaan dalam menghadapi krisis.
Tendensi tensi emosional masyarakat yang meningkat menimbulkan pola pikir, perubahan yang cepat, kalau bisa sekejap. Eksplosi emosional seperti ini tidak logis dan tidak realistis. Tidak mungkin kita bisa mengubah krisis ini dalam waktu sebulan, dua bulan atau bahkan setahun. Berbagai kambing hitam yang telah ditudingkan sebagai "faktor" krisis ini merupakan indikasi ketergesaan emosional masyarakat ini. Bila diformulasikan logika ketergesaan emosional masyarakat ini mungkin dapat diurutkan sebagai berikut: "Mengapa terjadi krisis? Siapa penyebabnya? Ganyang penyebabnya; beres masalahnya." Logika seperti ini tidak keliru, dan secara otomatis pasti ada dalam masyarakat, hanya tidak secara otomatis memecahkan permasalahan.
Keempat, kemelekatan atas predikat-predikat tertentu yang dinisbatkan orang kepada bangsa. Indonesia "terbelakang". Indonesia "tidak maju". Indonesia "tidak demokratis". Indonesia "tidak menguasai teknologi". Indonesia "kolusi dan korupsi".
Kemelekatan pada ide bahwa bangsa ini terbelakang dan tidak maju menimbulkan kebergantungan permanen pada bangsa yang "telah maju". Padahal jika para insinyur Indonesia di bawah pimpinan Menristek Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie telah berhasil membuat pesawat N-250, teknologi apa yang tidak bisa dikembangkan bangsa ini? Mobil nasional dengan 80% komponen dalam negeri ? Sepeda motor nasional dengan lebih dari 80% komponen dalam negeri? Berbagai teknologi digital, mulai dari industri rumah alarm dan peralatan elektronik hingga software dan konsultasi system engineering ? Tentunya semuanya bisa, bila pikiran bangsa kita tidak melekat pada ide-ide negatif tersebut. Amerika dan kekuatan-kekuatan raksasa di dunia telah terbukti menunggangi kuda sembrani "globalisasi", dan menebarkan jaring laba-laba perangkapnya pada seluruh bangsa di dunia. Perangkapnya adalah kemelekatan pada ide bahwa semua yang berbau Amerika dan kekuatan-kekuatan raksasa tersebut "maju, modern, demokratis, sahih, valid, trendy", dan lain-lain. Film? Hollywood. Komik? Disney atau Dragon Ball. Musik? Michael Jackson atau Phill Collins. Komputer? IBM. Makan? KFC atau McDonald atau Wendy's atau Pizza Hut. Busana? Giani Versace. Motor? Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Mobil? BMW, Mercedez, Mitubishi, Toyota, Honda. Minuman? Coca-Cola. Idola? Bill Gates ataupun Leonardo Di Caprio. Buku favorit? Toffler dan Drucker. Sentral telepon? Siemens. Instrumentasi elektronik? Schlumberger. Mesin-mesin berat? Mitsubishi. Software? Microsoft. Komputer IBM. Buah-buaha? Anggur atau apel Jepang. Otomatis bangsa-bangsa yang terperangkapp merasa dirinya "terbelakang", "tradisional", "otoriter", "kurang benar", "tidak valid", dan "tertinggal". Yah, adalah satu ironi bahwa penghasilan sebuah perusahaan burger terkenal di Amerika lebih besar dari RAPBN Indonesia. Demikianlah satu realitas dari apa yang diyakini (jangan baca diimani" secara membuta oleh orang banyak sebagai "globalisasi" yang akan membawa berkah fan kesejahteraan global. Ternyata telah menyebarkan jaring laba-laba ide-ide yang menjajah, yang telah sekian lama meninabobokan bangsa dengan lagu "kemajuan adalah GNP dan GNP Anda naik berkat "globalisasi"? dan menghancurkan pikiran kreatif bangsa. Dan itu semua benar-benar telah melekat erat dalam pikiran dan kehidupan bangsa.
Kelima, kemelekatan pada keengganan untuk berubah, padahal semua kondisi dengan terang mengatakan kita harus berubah, atau mati.
Orang selalu mengatakan, jika kita hendak berubah nanti kondisinya lebih buruk. Logika seperti ini seperti mengatakan "jangan naik kendaraan bermotor apapun, dan berjalan kakilahm agar tidak tertabrak". Pikiran ini jelas-jelas salah. Karena orang selayaknya selalu mengatakan jika kondisi ini tidak benar, maka kita harus berbuat yang lebih benar. Dan tentu kita yakin akan suatu prinsip kesegalaan yang sering disebut dengan devine justice alias Keadilan Ilahi. Yang baik akan menuai yang baik. Yang buruk akan menuai yang buruk. Namun bila kita mempunyai kesepakatan untuk mengubahnya, kita benar-benar memiliki suatu kans besar untuk mengubahnya.
Keenam, kemelekatan pada kultur-kultur dan cara berpikir masyarakat yang jelas-jelas salah. Budaya kolusi dan korupsi dalam berbagai proyek.
Budaya ABS (asal bapak senaang). Lemahnya institusi dan kekuatan hukum, maupun kesadaran masyarakat akan hukum. Budaya cuek terhadap permasalahan politik dan sosial, yang bahkan telah menghinggapi para pelajar sejak era NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus). Budaya mengacuhkan agama, syariat agama, dan aturan-aturan Tuhan. Bagaimana mungkin di negeri yang kebanyakan adalah muslim, yang percaya hukum Tuhan, pabrik bir bisa beroperasi dengan lancar, budaya wine (anggur) menyerbu kalangan elit, acara-acara TV yang tidak layak mengisi sebagian besar kehidupan masyarakat, prostitusi diizinkan beroperasi dan berbagai sumber-sumber kemaksiatan lain? Mengapa banyak orang yang enggan untuk mengakui, seperti yang diserukan oleh Mas Amien Rais, bahwa kita harus melakukan tobat nasional. Bertobat atas seluruh cara berpikir dan kultur-kultur yang benar-benar salah dan kesalahannya tak perlu dibuktikan lagi (self-evident).
Ketujuh, untuk mengembalikan kepercayaan (trust) dalam masyarakat, yang menurut Francis Fukuyama merupakan faktor kunci untuk mencapai masa itu, maka bangsa ini harus segera melepaskan diri dari semua keterlekatan dan kembali kepada prinsip-prinsip alami yang swa-bukti, yakni justice (keadilan), honesty (kesederhanaan), fair-play. Covey, dalam bukunya Managing by Principles, hanyalah pemimpin yang kembali pada prinsip-prinsip yang kembali pada prinsip-prinsip alami swa-bukti ini. Prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan seluruh makro dan mikrokosmos ini, dan yang menentangnya akan sirna. Dalam istilah Darwiniannya, the survival of the fittest (survivalitas yang paling cocok dengan alam). Dan bila bangsa Indonesia tidak segera melepaskan diri dari seluruh kemelekatan dan kemudian bersegera untuk kembali pada prinsip-prinsip niscaya yang alamiah ini, berarti bangsa Indonesia akan segera sirna?
Penulis adalah dosen teknik eletro ITB kelahiran 1968 di Semarang dengan catatan prestasi sebagai berikut: mahasiswa terbaik ITB tahun 1989, wisudawan terbaik-cumlaude tahun 1989, dan meraih gelar Master of Engineering di Waseda University, Tokyo dengan straight-A mark pada tahun 1994 dan Doktor dengan predikat cumlaude di ITB pada tahun 1998. Saat ini, selain sebagai dosen juga aktif berbicara di forum-forum internasional dan nasional di bidang Automation, Robotics and Computer Vision, serta aktif menulis di berbagai media-massa cetak dan berbicara di media TV dengan topik: trend teknologi, futuristik dan prospek masa depan. [di Sadur dari Menjemput Masa Depan, 1999]
oleh Dr.Ir. Dimitri Mahayana, M.Sc.
7 Mitos Penghambat Kemandirian. Entah angin apa yang mengantar saya pada Folder koleksi Artikel, dan menemukan tulisan yang menurut saya inspirasi untuk membangun kemandirian personal maupun bangsa. Tulisan sederhana yang senantiasa menyemangati gerak keseharian kita, khususnya bagi pebisnis, akademisi, intelektual, "politisi", petualang dan siapapun yang ingin belajar dan berpikiran maju. Judul postingan, adalah murni subjektifitas saya (alamyin) tidak ada maksud selain berbagi inspirasi. Selamat membaca.
Judul asli tulisan ini adalah TORAWARENAI SUNAONA KOKORO (Pikiran yang Tidak Melekat) ditulis oleh Dr.Ir. Dimitri Mahayana, M.Sc.
Konosuke Matsushita, pendiri korporasi raksasa Jepang Matshushita, mempunyai satu prinsip filosofis manajemen yang amat terkenal; "Torowarenai sunaona kokoro, (pikiran [hati] yang tidak melekat)". Matsushita yakin seorang pemimpin harus benar-benar memiliki kebeningan hati, kecerahan pikiran, dan ke-tidakmelekat-an pikiran dan hati agar dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang tepat.
Kemelekatan IBM dengan industri komputer mainframe-nya, misalnya, telah membuat para pimpinannya membatasi penjualan PC (Personal Computer) - yang dikhawatirkan akan merusak pasar komputer mainframe- sehingga akhirnya IBM tidak bisa leading dalam industri PC di dunia, padahal ia termasuk yang paling awal menguasai teknologi PC. Dan apa yang terjadi? PC ternyata menjadi satu dengan kehidupan masyarakat global. IBM telah menyia-nyiakan pasar masa depan hanya karena kemelekatannya dengan masa lalunya. Berpikir tentang krisis moneter akhir-akhir ini ala Matsushita, kita mesti meninggalkan ke-melekat-an pikiran dan persepsi bangsa atas beberapa aspek berikut.
Pertama, kemelekatan atas bayangan-bayangan "sukses" pembangunan nasional di masa sebelum krisis.
Analisis-analisis para pakar ekonomi dari Bank Dunia, IMF, telah lama meninabobokkan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan angka-angka yang fantastis. Mereka mensugesti Indonesia dengan "kenyataan" bahwa pertumbuhan ekonomi nasional 7 hingga 8% setahun dengan laju inflasi kurang dari dua digit. Bangsa Indonesia dan negara-negara sedang berkembang lain mesti melepaskan diri dari khayalan-khayalan "sukses" semacam ini, dan segera menyadari kondisi objektif yang benar-benar riil. Dengan kesadaran ini, kejernihan melakukan langkah yang tepat dalam menanggulangi krisis dapat diperoleh.
Kedua, kemelekatan pada nowism (kekinian) dan menyibukkan diri dengan melihat kurs dolar maupun jumlah orang yang di-PHK tiap hari dan merenungkannya, kemudian menenggelamkan diri dengan berbagai isu-isu dan rumor-rumor yang tidak jelas arah dan sumbernya.
Akan sangat banyak energi yang terbuang sia-sia jika bangsa ini terjebak pada pola over-analysis dan over-observation sehingga malah tidak segera mengambil tindakan apa pun. Apakah dengan nilai dolar setiap hari berubah, seorang bussinesmen mesti mengubah bisnisnya setiap hari? Atau apakah semua orang mesti terjun beramai-ramai bermain valas, sehingga bangsa akan memakan dolar sebagai ganti beras? Apakah dengan menangisi orang-orang yang di-PHK semuanya akan beres?
Ketiga, kemelekatan pada ketergesaan dalam menghadapi krisis.
Tendensi tensi emosional masyarakat yang meningkat menimbulkan pola pikir, perubahan yang cepat, kalau bisa sekejap. Eksplosi emosional seperti ini tidak logis dan tidak realistis. Tidak mungkin kita bisa mengubah krisis ini dalam waktu sebulan, dua bulan atau bahkan setahun. Berbagai kambing hitam yang telah ditudingkan sebagai "faktor" krisis ini merupakan indikasi ketergesaan emosional masyarakat ini. Bila diformulasikan logika ketergesaan emosional masyarakat ini mungkin dapat diurutkan sebagai berikut: "Mengapa terjadi krisis? Siapa penyebabnya? Ganyang penyebabnya; beres masalahnya." Logika seperti ini tidak keliru, dan secara otomatis pasti ada dalam masyarakat, hanya tidak secara otomatis memecahkan permasalahan.
Keempat, kemelekatan atas predikat-predikat tertentu yang dinisbatkan orang kepada bangsa. Indonesia "terbelakang". Indonesia "tidak maju". Indonesia "tidak demokratis". Indonesia "tidak menguasai teknologi". Indonesia "kolusi dan korupsi".
Kemelekatan pada ide bahwa bangsa ini terbelakang dan tidak maju menimbulkan kebergantungan permanen pada bangsa yang "telah maju". Padahal jika para insinyur Indonesia di bawah pimpinan Menristek Prof. Dr. Ing. B.J.Habibie telah berhasil membuat pesawat N-250, teknologi apa yang tidak bisa dikembangkan bangsa ini? Mobil nasional dengan 80% komponen dalam negeri ? Sepeda motor nasional dengan lebih dari 80% komponen dalam negeri? Berbagai teknologi digital, mulai dari industri rumah alarm dan peralatan elektronik hingga software dan konsultasi system engineering ? Tentunya semuanya bisa, bila pikiran bangsa kita tidak melekat pada ide-ide negatif tersebut. Amerika dan kekuatan-kekuatan raksasa di dunia telah terbukti menunggangi kuda sembrani "globalisasi", dan menebarkan jaring laba-laba perangkapnya pada seluruh bangsa di dunia. Perangkapnya adalah kemelekatan pada ide bahwa semua yang berbau Amerika dan kekuatan-kekuatan raksasa tersebut "maju, modern, demokratis, sahih, valid, trendy", dan lain-lain. Film? Hollywood. Komik? Disney atau Dragon Ball. Musik? Michael Jackson atau Phill Collins. Komputer? IBM. Makan? KFC atau McDonald atau Wendy's atau Pizza Hut. Busana? Giani Versace. Motor? Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki. Mobil? BMW, Mercedez, Mitubishi, Toyota, Honda. Minuman? Coca-Cola. Idola? Bill Gates ataupun Leonardo Di Caprio. Buku favorit? Toffler dan Drucker. Sentral telepon? Siemens. Instrumentasi elektronik? Schlumberger. Mesin-mesin berat? Mitsubishi. Software? Microsoft. Komputer IBM. Buah-buaha? Anggur atau apel Jepang. Otomatis bangsa-bangsa yang terperangkapp merasa dirinya "terbelakang", "tradisional", "otoriter", "kurang benar", "tidak valid", dan "tertinggal". Yah, adalah satu ironi bahwa penghasilan sebuah perusahaan burger terkenal di Amerika lebih besar dari RAPBN Indonesia. Demikianlah satu realitas dari apa yang diyakini (jangan baca diimani" secara membuta oleh orang banyak sebagai "globalisasi" yang akan membawa berkah fan kesejahteraan global. Ternyata telah menyebarkan jaring laba-laba ide-ide yang menjajah, yang telah sekian lama meninabobokan bangsa dengan lagu "kemajuan adalah GNP dan GNP Anda naik berkat "globalisasi"? dan menghancurkan pikiran kreatif bangsa. Dan itu semua benar-benar telah melekat erat dalam pikiran dan kehidupan bangsa.
Kelima, kemelekatan pada keengganan untuk berubah, padahal semua kondisi dengan terang mengatakan kita harus berubah, atau mati.
Orang selalu mengatakan, jika kita hendak berubah nanti kondisinya lebih buruk. Logika seperti ini seperti mengatakan "jangan naik kendaraan bermotor apapun, dan berjalan kakilahm agar tidak tertabrak". Pikiran ini jelas-jelas salah. Karena orang selayaknya selalu mengatakan jika kondisi ini tidak benar, maka kita harus berbuat yang lebih benar. Dan tentu kita yakin akan suatu prinsip kesegalaan yang sering disebut dengan devine justice alias Keadilan Ilahi. Yang baik akan menuai yang baik. Yang buruk akan menuai yang buruk. Namun bila kita mempunyai kesepakatan untuk mengubahnya, kita benar-benar memiliki suatu kans besar untuk mengubahnya.
Keenam, kemelekatan pada kultur-kultur dan cara berpikir masyarakat yang jelas-jelas salah. Budaya kolusi dan korupsi dalam berbagai proyek.
Budaya ABS (asal bapak senaang). Lemahnya institusi dan kekuatan hukum, maupun kesadaran masyarakat akan hukum. Budaya cuek terhadap permasalahan politik dan sosial, yang bahkan telah menghinggapi para pelajar sejak era NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus). Budaya mengacuhkan agama, syariat agama, dan aturan-aturan Tuhan. Bagaimana mungkin di negeri yang kebanyakan adalah muslim, yang percaya hukum Tuhan, pabrik bir bisa beroperasi dengan lancar, budaya wine (anggur) menyerbu kalangan elit, acara-acara TV yang tidak layak mengisi sebagian besar kehidupan masyarakat, prostitusi diizinkan beroperasi dan berbagai sumber-sumber kemaksiatan lain? Mengapa banyak orang yang enggan untuk mengakui, seperti yang diserukan oleh Mas Amien Rais, bahwa kita harus melakukan tobat nasional. Bertobat atas seluruh cara berpikir dan kultur-kultur yang benar-benar salah dan kesalahannya tak perlu dibuktikan lagi (self-evident).
Ketujuh, untuk mengembalikan kepercayaan (trust) dalam masyarakat, yang menurut Francis Fukuyama merupakan faktor kunci untuk mencapai masa itu, maka bangsa ini harus segera melepaskan diri dari semua keterlekatan dan kembali kepada prinsip-prinsip alami yang swa-bukti, yakni justice (keadilan), honesty (kesederhanaan), fair-play. Covey, dalam bukunya Managing by Principles, hanyalah pemimpin yang kembali pada prinsip-prinsip yang kembali pada prinsip-prinsip alami swa-bukti ini. Prinsip-prinsip yang mengatur kehidupan seluruh makro dan mikrokosmos ini, dan yang menentangnya akan sirna. Dalam istilah Darwiniannya, the survival of the fittest (survivalitas yang paling cocok dengan alam). Dan bila bangsa Indonesia tidak segera melepaskan diri dari seluruh kemelekatan dan kemudian bersegera untuk kembali pada prinsip-prinsip niscaya yang alamiah ini, berarti bangsa Indonesia akan segera sirna?
Penulis adalah dosen teknik eletro ITB kelahiran 1968 di Semarang dengan catatan prestasi sebagai berikut: mahasiswa terbaik ITB tahun 1989, wisudawan terbaik-cumlaude tahun 1989, dan meraih gelar Master of Engineering di Waseda University, Tokyo dengan straight-A mark pada tahun 1994 dan Doktor dengan predikat cumlaude di ITB pada tahun 1998. Saat ini, selain sebagai dosen juga aktif berbicara di forum-forum internasional dan nasional di bidang Automation, Robotics and Computer Vision, serta aktif menulis di berbagai media-massa cetak dan berbicara di media TV dengan topik: trend teknologi, futuristik dan prospek masa depan. [di Sadur dari Menjemput Masa Depan, 1999]












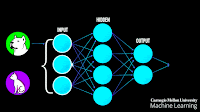
0 comments:
Post a Comment